Mengapa santri harus menulis? Di dalam sebagian riwayat disebutkan agar ilmu itu sendiri tidak hilang. Seperti yang dijelaskan dalam kitab populer Ta’limul Muta’alim Thariq at Ta’allum karya Imam al-Zarnuji, ilmu itu bagaikan hewan buruan, sedangkan tulisan adalah tali pengikatnya, maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat.
Dalam kitab al-Mu’jam al-Kabir (no. 936), diriwayatkan dari al-Tabrani dari Abdullah bin Umar ra., beliau bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, apakah ilmu harus diikat?”
Rasulullah menjawab, “Ya,” lalu ditanya lagi, “apa pengikatnya, Ya Rasulullah?”
“Buku (tulisan),” jawab Rasulullah.
Juga kita dapat temukan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Surah Al-Alaq 1-5 terdapat ayat yang menyebutkan bahwa Allah ialah Dzat yang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan pena, Dia (Allah) mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Lalu ada lagi sebuah adagium yang konon pertama kali dikemukakan oleh Winston Churcill berbunyi, “History has been written by the victors” [Sejarah ditulis oleh para pemenang]. Konon Winston adalah salah satu tokoh yang mendominasi asersi modern dan post modern mengenai natur dari sejarah.
Arti dari berbagai kutipan diatas mungkin sudah cukup untuk kita jadikan landasan bahwa menulis membuat seseorang abadi. Abadi disini bukan berarti orang tersebut tidak mati. Akan tetapi orang yang menulis, dan hasil tulisannya masih digunakan untuk khalayak umum maka keberkahan dan kebermanfaatan dari orang yang mempelajari hasil tulisannya mengalir kepada sang penulis. Atau bisa juga kita sebut, raganya saja yang tiada namun buah akal pikirannya masih ada.
Lalu mengapa santri identik dengan menulis catatan atau dalam bahasa pondok pesantrennya maknai, padahal sudah banyak kitab terjemahan, sehingga santri tidak perlu repot-repot menulis, dan menambal makna kitab yang kosong.
Perlu diketahui bahwa aktivitas menulis bagi santri tidak hanya rutinitas yang wajib ia lakukan, namun juga sebagai laku tunduk kepada sang guru atau ustaz yang mengajar. Bisa dibayangkan, ketika tengah bandongan atau memaknai kitab langsung dari apa yang guru bacakan, santri harus fokus dan memerhatikan apa yang gurunya bacakan. Nah, posisi badan membungkuk atau menunduk ketika menulis bisa kita maknai sebagai wujud perilaku tunduk dan hormat pada sang guru.
Lalu mengapa pena khas santri harus selalu yang tajam ujungnya, dan tidak boleh memakai tinta warna merah. Asal diketahui, terkadang kecepatan membaca seorang guru melebihi kecepatan menulis para santri itu sendiri. Itulah sebabnya untuk tingkatan santri yang sudah mahir, ia tidak menuliskan semua yang gurunya ucapkan. Melainkan hanya makna-makna dari mufradat yang ia tidak ketahui, dan bisa juga mengenai kedudukan kata tersebut dalam ilmu nahwu dan sharf.
Oleh karena ketajaman dari pena berpengaruh pada makna yang tertulis di kitab, maka dianjurkan memakai pena yang ujungnya tajam agar memudahkan tulisan untuk dibaca ulang, dan merapihkan tulisan. Tahu kan rasanya membaca tulisan yang amburadul dan bercetak tebal sehingga sulit membacanya, baru melihat saja sudah enggan melihat, apalagi kalau harus disuruh membaca ulang? (eitss, yang dimaksud tajam disini tidak sampai setajam pisau untuk mengupas kulit mangga, ya).
Lalu berkenaan dengan tinta merah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan, salah satunya dalam kitab karangan Imam Az-Zarnuji bahwa menulis dengan menggunakan tinta merah adalah kebiasaan dari orang filosof, bukan perbuatan dari para salaf (ilmuan terdahulu), maka sebaiknya dihindari karena hal itu merupakan sebagian dari adab menuntut ilmu.
Dan kali ini argumen terakhir diambil dari ungkapan yang sebelumnya telah disebutkan, bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Kok sinis amat ungkapannya? Tapi inilah kenyataanya, pemenang menulis sejarah untuk membenarkan tindakannya, sekaligus menyalahkan semua tindakan kaum yang dikalahkan.
Masih teringat jelas di benak penulis, satu tahun lalu ketika munculnya buku berjudul “Menjerat Gus Dur” karya Virdika Rizky Utama. Siapa yang menyangka sejarah yang begitu besar dapat diungkapkan di balik kertas dokumen bekas, bertahun tahun setelah banyak orang melupakannya. Ini memperkuat kutipan dari Adolf Hitler bahwa kebenaran adalah 1000 kebohongan yang diulang berkali-kali.
Juga kasus lain mengenai pembantaian pasca peristiwa G-30 S/PKI, menurut Amnesti Internasional lebih dari 1,2 juta orang tewas sia-sia. Sedangkan di Pangkopkamtib Soedomo hanya disebutkan sekitar 600 ribu jiwa saja. Bagaimanapun juga, pembantaian jiwa anak bangsa tanpa pengadilan adalah perbuatan sangat biadab dan dalam ajaran Islam itu ialah perbuatan yang dilarang oleh agama.
Dari beberapa kisah di atas, nampaknya jelas bukan mengapa santri juga harus pandai menulis, salah satunya agar ia bisa jadi pelaku sejarah yang menegakkan keadilan di negaranya. Sedangkan untuk keluarga dan lingkungannya, diharapkan santri bisa turut andil menyebarkan gagasan-gagasan segar dan mewaraskan jiwa di tengah zaman yang hiruk pikuk dan banyak informasi yang sehari-hari kita terima. Untuk itu, semoga dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2021, santri nantinya tidak hanya dikenal sebagai kaum sarungan dan ahli dzikir namun juga sebagai agent of change yang senantiasa tumbuh, berdaya dan berkarya. Wallahu’alam bi shawab.
Oleh: Khoirun Nisaa
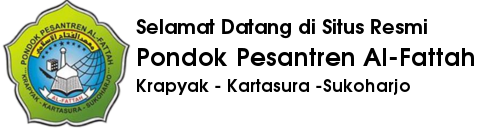






Add Comment