Dahulu, kira-kira bulan Februari, ada seorang ustaz yang terang-terangan mengaku bahwa dirinya baru saja menabrak seekor anjing di jalan sampai pincang. Barangkali bagi ustaz tersebut—dan bagi kita umumnya, anjing adalah hewan yang najis dan sama sekali tak berharga dibanding hewan-hewan lainnya. Kemudian dengan anggapan begitu, maka sah-sah saja kita melakukan apapun terhadap anjing tersebut. Hanya satu hewan yang sama hinanya dengan anjing, yaitu babi. Begitulah kira-kira stereotip umum kita.
Anjing dalam Literatur Fikih
Anjing sebagai hewan najis adalah pemahaman kita secara yurisprudensi Islam, atawa fikih. Dapat kita baca di dalam kitab fikih syafi’iyah, misalnya kitab fikih dasar, Safinah al-Najah namanya, secara gamblang menyebutkan anjing dan babi adalah dua najis mughalazhah yang penyuciannya harus dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan debu. Kurang lebih begitu keterangannya.
Dengan demikian, untuk menjaga kesucian badan kita, maka kita mesti menjauhi dua hewan—dan peranakannya tersebut, kecuali jika kamu ndak keberatan bersuci dengan membasuh tujuh kali tanganmu itu, misalnya, yang menyentuh atau dijilati anjing. Ingat, salah satu dari tujuh basuhan itu mesti pakai debu. Selesai.
Kemudian, hanya karena hewan yang najis, bolehkah kita melukai atau membunuh anjing (dan babi)? Kita dapat membacanya lebih jauh dalam Kasyifah al-Saja, sebuah anotasi Safinah al-Najah karangan Syaikh Nawawi Banten.
Di sana, Syaikh Nawawi membagi anjing menjadi 3; pertama, al-‘aqur yang berarti anjing liar dan galak. Hukum membunuhnya adalah sunnah. Kedua, anjing yang dilatih untuk berburu atau penjaga. Anjing jenis ini haram hukumnya untuk dibunuh, dan ketiga, al-ju’ashi atau anjing pasar, yaitu yang tidak liar dan tidak juga terlatih, maka mengenai ini para ulama berbeda pendapat, namun menurut al-Ramly hukum membunuhnya adalah haram.
Anjing dalam Literatur Jawa
Dalam khazanah susastra Jawa, kita tahu, ada banyak sekali suluk atau pun serat yang digubah oleh para wali dan sunan. Misalnya Serat Wirid Hidayat Jati, Suluk Saloka Jiwa, Serat Pamoring Kawula-Gusti, Serat Wedhatama, Suluk Malang Sumirang dan lain sebagainya.
Di antara karya-karya wali-sunan yang saya sebutkan, saya ndak akan membahas semuanya. Saya hanya akan menyinggung karya yang ada kaitannya dengan tema tulisan—bukan tulisan sebenarnya, lebih tepatnya nggedibal—ini.
Ada cerita menarik yang dicatat oleh George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019) (karya ini sudah diterbitkan oleh Kepustakaan Gramedia Populer (KPG) dalam bahasa Indonesia dengan judul Wali Berandal Tanah Jawa (2021), yaitu cerita Pangeran Panggung, bersama kedua anjingnya, Iman dan Tokid, yang tak mempan dibakar dalam unggunan api.
Singkat cerita, Sultan Trenggana, penguasa Demak kala itu adalah adik Pangeran Panggung. Sultan telah menerima laporan bahwa kakaknya tenggelam dalam perenungan terhadap Yang Mahatinggi hingga perilakunya menjadi tidak keruan dan tak peduli dengan hukum dan aturan, bahkan al-Quran.
Payahnya lagi, Pangeran Panggung memelihara dua anjing, satu berwarna hitam yang dinamai Iman dan yang satu kemerah-merahan, Tokid namanya. Ke mana pun sang pangeran pergi, kedua anjingnya ikut. Bahkan ikut Jumatan di masjid, duduk di belakang tuannya, dan turut belajar hukum Nabi dengan tekun.
Hingga akhirnya kabar itu sampai ke telinga Walisanga yang segera meminta kepada Kanjeng Sultan Trenggana untuk menindak tegas kakaknya itu, khawatir jika terus-terusan begitu, hukum agama akan kehilangan wibawa bahkan merusak fondasi Islam di Demak.
Setelah Walisanga berunding, keluarlah keputusan untuk membakar hidup-hidup Pangeran Panggung dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Demak.
Tibalah saatnya Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup di tengan alun-alun.
Mulanya, Pangeran Panggung melepaskan sendalnya dan melemparkannya ke dalam api. Kemudian dia bersiul ke anjingnya, Iman dan Tokid, dan mereka berlari memasuki api. Layaknya anjing yang diberi mainan oleh tuannya, Iman dan Tokid bermain-main sendal tuannya di dalam api.
Lalu setelah Pangeran Panggung memberi isyarat, Iman dan Tokid segera kembali kepadanya, dengan membawa sendal di masing-masing mulutnya.
“Sekarang giliranmu. Masuklah ke api. Jangan hanya anjingmu!” perintah Sultan. Dan Pangeran Panggung dengan santainya memasuki unggunan api tanpa protes apapun.
Sesampainya di tengah unggunan api, Pangeran Panggung menancapkan tongkatnya di tanah dan mulai menulis sebuah suluk di tengah kobaran api. Suluk tersebut kemudian dikenal dengan Suluk Malang Sumirang, sebuah karya yang diakui Quinn sebagai karya luar biasa.
Anjing dalam Tasawuf
Rupanya, Iman dan Tokid, dua anjing Pangeran Panggung tersebut adalah penjelamaan dua nafsu (lauwamah dan amarah) yang telah berhasil diusir Pangeran Panggung dari dalam dirinya, yang kemudian dikenang menjadi sahabat setianya. Nama yang dia berikan kepada dua anjingnya menunjukkan dua gagasan lain yang juga sempat dibuangnya; keyakinan terhadap kebenaran agama (iman) dan kepercayaan pada teologi ortodoks Islam (tauhid, atau dalam pelafalan Jawa menjadi tokid).
Perumpaan atau perlambangan anjing dalam cerita di atas sama persis dengan praktik-praktik sufisme dalam literatur tasawuf terkait dengan upaya tazkiyatun-nafs, penyucian jiwa seorang hamba.
Semukabalah dengan itu, Syaikh Nawawi, dalam Kasyifah al-Saja, juga menyebutkan sepuluh sifat anjing yang menjadi perlambangan bagi seorang hamba yang dimabuk cinta pada Tuhannya. Layaknya anjing bagi tuannya; setia dicampakkan, rida meski disakiti, sabar meski disia-siakan, dan terima dengan apa yang diberikan kepadanya.
Walakhir, sangat salah bila kita menganggap anjing adalah sehina-hinanya hewan, apalagi makhluk Allah. Tidakkah kita tahu piaraan Ashabul Kahfi yang konon masuk surga itu adalah anjing? Tidakkah kita tahu kisah seorang pelacur yang diberi rahmat Allah berupa surga hanya sebab memberi minum seekor anjing?
Wallahu a’lam..
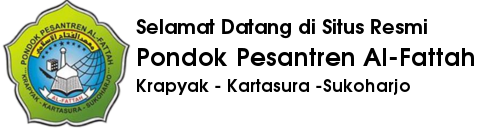






Tulisan yang sangat menarik dan membuka mata hati kita bahwa tidak selamanya anjing itu haram semuanya
terima kasih kakak…